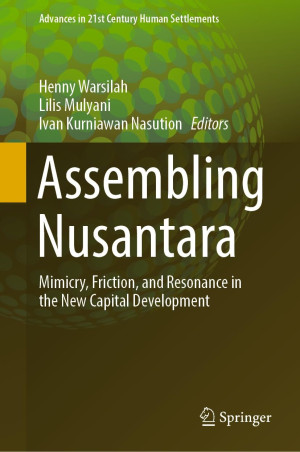Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*
Judul lengkapnya "Indonesia Out of Exile: How Pramoedya's Buru Quartet Killed a Dictatorship", sebuah buku baru diterbitkan Penerbit Pinguin yang ditulis Max Lane, peneliti dan aktifis Australia yang sejak akhir tahun 1970an telah melibatkan dirinya dalam kemelut politik Indonesia.
Buku ini merupakan karyanya yang paling mutakhir yang menggambarkan keterlibatannya yang dalam dengan politik Indonesia yang menjadi sangat represif sejak 1965. Penculikan dan pembunuhan sejumlah Jendral pada tengah malam sampai menjelang pagi pada tanggal 30 September 1965 itu telah dijadikan alasan untuk menumpas habis hingga ke-akar-akarnya golongan kiri di Indonesia.
Marxisme, salah satu isme dari tiga isme yang pernah ditulis Bung Karno muda tahun 1926 ketika usianya masih 25 tahun, sejak 1965 menjadi momok yang tak punya hak hidup di Indonesia. Ketiga isme yang dikemukakan Bung Karno di Harian Suluh Indonesia Muda 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda (1928) dan pada tahun yang sama saat terjadi pemberontakan komunis di Banten dan Sumatera Barat melawan kolonialisme; itu adalah: Islam, Marxisme dan Nasionalisme.
Setelah tahun 1965 Indonesia seperti berjalan dengan dua kaki, ketika salah satu kakinya diamputasi oleh Suharto. Sejak itu Indonesia sesungguhnya tumbuh dengan kaki baru, kapitalisme plus militerisme.
Sejarah gerakan politik dan nasionalisme Indonesia yang dimulai awal abad 20 dan melewati tonggak-tonggak penting 1908, 1928,1945 seperti terhenti pada tahun 1965. Sebagai bagian dari pembasmian komunisme adalah diasingkannya ribuan mereka yang dianggap komunis ke Pulau Buru di Maluku. Menarik bagaimana pemerintahan Suharto memilih Pulau Buru sebagai gulag Indonesia.
Pengasingan sebagai strategi untuk melumpuhkan kekuatan orang-orang yang bisa mengguncang kekuasaan telah dijalankan sebelumnya oleh Belanda. Saat itu juga mereka yang dianggap komunis setelah terjadi perlawanan bersenjata di Banten dan Sumatera Barat tahun 1926. Para nasionalis itu diasingkan ke Boven Digoel di Papua. Mereka yang dituduh komunis dan dianggap terlibat pada pemberontakan 1926 itu baru dibebaskan ketika tentara Jepang menduduki Indonesia dengan mengungsikan mereka ke Australia. Sebagian dari mereka baru kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan.
Pengasingan sebagai politik migrasi dengan demikian telah dimulai oleh Belanda. Ketika pemerintahan militer Orde Baru di bawah Jendral Suharto menggunakan politik migrasi untuk mengasingkan mereka yang dianggap komunis setelah peristiwa 1965 dengan demikian mengulang sejarah kolonialisme. Bedanya setelah 1965 kolonialisme itu dilakukan oleh penguasa terhadap bangsanya sendiri. Inilah ironi sejarah Indonesia.
Max Lane sengaja menyusun bab-bab dalam buku ini dengan tujuan menarik pembaca muda untuk masuk dalam sejarah penting bangsanya. Sebuah penggalan sejarah yang selama ini sengaja dikubur untuk menghilangkan jejak penindasan oleh sebuah pemerintahan diktator militer terhadap bangsanya sendiri. Dengan Pramoedya Ananta Toer, seorang novelis, sebagai tokoh kunci yang ikut diasingkan ke Pulau Buru dan menjalani kerja paksa (forced Labor) lebih dari 10 tahun disana. Max Lane dalam buku barunya ini menunjukkan bagaimana politik migrasi menghasilkan sebuah perlawanan puitik melalui kwartet novel Pulau Buru.
"Out of Exile" adalah sebuah bentuk politik perlawanan terhadap rejim penindas tanpa menggunakan senjata, tanpa mengandalkan kekerasan, sebuah perlawanan puitik. Melalui empat buku yang ditulisnya dalam masa pembuangan di kepulauan gulag Indonesia, Pramoedya dengan cara yang hampir mustahil secara menakjubkan menuliskan keempat novel Pulau Buru-nya. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca; adalah kisah bersambung dengan tokoh Minke, yang diinspirasi oleh tokoh sejarah, jurnalis pertama Indonesia, Tirto Ardisoerjo. Tirto Adisoerjo juga diasingkan oleh Belanda ke Ternate.
Pengasingan dan pembuangan adalah bentuk "forced migration", politik migrasi yang terbukti ditiru oleh rejim Orde Baru setelah sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pulau Buru sebagai tempat pembuangan ribuan tahanan politik yang dituduh sebagai komunis bisa dilihat sebagai bentuk kolonisasi rejim Orde Baru. Orde Baru juga meneruskan kebijakan emigrasi Belanda menjadi program transmigrasi besar-besaran, pemindahan penduduk Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa yang dianggap kosong, sepert Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku dan Papua.
Migrasi adalah strategi politik Orde Baru untuk meng-kolonisasi nusantara. Dalam pandangan Jendral Suharto orang-orang di luar Jawa perlu di-Jawa-kan agar Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang selaras dan harmonis.
Politik migrasi Orde Baru memperoleh perlawanan puitik dari tempat pembuangan berupa cerita dari Buru tentang fajar kebangsaan yang berhasil diselundupkan dan diterbitkan oleh Hasta Mitra, sebuah lembaga intelektual yang didirikan tiga serangkai tapol yakni Joesoef Iskak, Pramoedya Ananta Toer dan Hasjim Rachman. Dengan sangat menarik Max Lane menggambarkan bagaimana tiga serangkai itu menggerakkan Hasta Mitra, lagi-lagi dengan niat melawan represi dengan resistensi puitik-nya.
Ke-empat novel Pramoedya yang bermigrasi mengarungi laut, "Out of Exile", seperti lepas dari rantai besi yang membelenggunya, merasuk seperti benang-benang sutera yang halus menyelinap dalam benak para pembacanya, sebagian besar anak muda dan menjadi puisi perlawanan yang indah, menginspirasi gerakan protes pemuda dan mahasiswa, menggulingkan kediktatoran yang selama tiga dekade telah menindas bangsanya sendiri.
Membaca buku ini hari ini, seharusnya mengingatkan kita semua bahwa penindasan itu, kediktoran itu, sesungguhnya belum benar-benar tumbang apalagi mati. Ibarat Rahwana dalam dunia pewayangan kediktatoran itu hanya berubah muka, hatinya tetap sama, tingkah lakunya sama, menindas bangsanya sendiri.
*Kampung Limasan Tonjong, 30 September 2023. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo tentang pelbagai topik dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com
Editor. KJ-JP